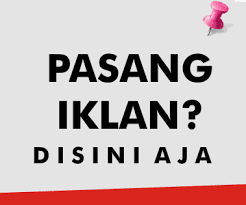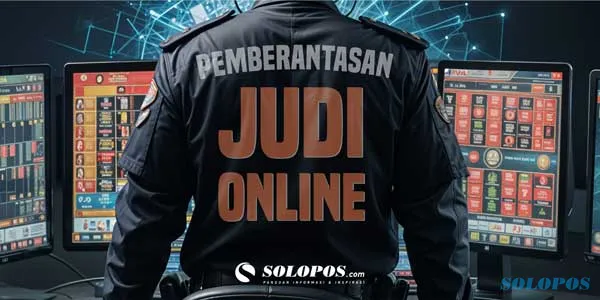Oleh: Margo Noff Ra )*
Hari Pahlawan selalu mengingatkan kita bahwa republik berdiri di atas kerja memori kolektif. Siapa yang kita ingat, bagaimana kita mengingat, dan mengapa ingatan itu layak diberi status kehormatan. Dalam horizon itu, dukungan sejumlah tokoh agama, akademisi, dan politisi agar negara menimbang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto patut dibaca bukan sebagai ajakan melupakan luka, melainkan sebagai undangan menata ingatan secara matang. Politik ingatan yang dewasa tidak menghapus ambivalensi sejarah, namun menimbang kontribusi dengan ukuran publik yang jelas, berbasis bukti, serta berpihak pada ketahanan republik.
Dari sudut etik keagamaan, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengajukan parameter yang relevan bahwa setiap mantan presiden yang telah wafat memiliki kelayakan untuk dinilai jasa-jasanya sebagai pahlawan karena telah memikul beban pengabdian negara. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada dendam historis—sebuah dorongan etis untuk melepaskan afek yang mengaburkan penilaian. Bagi kajian kebudayaan, hal inj menyentuh “etika pengakuan” dimana kemampuan komunitas politik mengakui jasa tanpa menafikan kritik, dan mengkritik tanpa meniadakan jasa. Di sini, lensa yang ditawarkan bukan amnesia, melainkan forensic remembrance—ingatan yang cermat, proporsional, dan bertanggung jawab.
Dari ranah organisasi keislaman, suara serupa datang dari Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai kontribusi Soeharto bersifat historis sekaligus strategis. Penekanan pada peran di masa revolusi—termasuk keterlibatan dalam perang gerilya dan momentum Serangan Umum 1 Maret 1949—mengembalikan diskursus pada premis awal republik bahwa pengakuan kedaulatan di mata dunia dibentuk oleh kerja militer-sipil yang sinkron. Secara teoretik menyentuh “genealogi kedaulatan”, narasi tentang bagaimana tindakan-tindakan strategis pada fase rapuh negara memberi efek legitimasi jangka panjang. Dalam tata bahasa Hari Pahlawan, kontribusi semacam itu berada di inti logika penghargaan.
Sementara itu, dari jajaran pemerintah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggarisbawahi aspek pembuktian historis terkait tuduhan pelanggaran HAM 1965–1966. Sebuah gelar negara harus berdiri di atas verifikasi, bukan insinuasi dan penting bukan untuk menutup kritik, tetapi untuk memastikan bahwa narasi penghukuman atau penganugerahan sama-sama tunduk pada standar bukti. Dengan begitu, pendidikan sejarah kita terhindar dari trial by rumor yang merusak kapasitas publik berpikir jernih.
Dukungan juga datang dari ranah politik kebijakan. Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menekankan stabilitas politik pada era Orde Baru dan capaian swasembada pangan sebagai indikator penting menyentuh memori keseharian yang kerap menjadi basis legitimasi—bukan hanya narasi heroik, tetapi pengalaman hidup warganegara atas keamanan, pasokan pangan, dan keteraturan ekonomi.
Dari ruang akademik, suara Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti mengajak publik menatap capaian-capaian objektif selama tiga dekade kepemimpinan. Bangsa yang dewasa tidak menyederhanakan sejarah ke dalam dikotomi malaikat-setan, melainkan menyusun matriks penilaian yang menimbang dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan publik, infrastruktur, dan kesinambungan institusi.
Karena itu, negara menimbang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto yang telah diiringi protokol transparansi, pembukaan arsip yang relevan, panel penilaian lintas-disiplin, dan komunikasi publik yang menjelaskan indikator serta rasionalitas keputusan. Penghargaan ini peneguhan standar—bahwa republik bisa mengakui jasa besar sembari tetap memelihara ruang kritik.
Hari Pahlawan selalu menuntun kita pada etika pengakuan—bahwa sejarah bangsa bukan deret nama yang disakralkan, melainkan mozaik pencapaian dan luka yang diolah secara dewasa. Dalam bingkai itu, menimbang jasa Soeharto berarti menempatkan diri pada horizon keadilan memori untuk mengakui kontribusi strategisnya dalam konsolidasi negara-bangsa, stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan modernisasi birokrasi—seraya tetap membuka ruang kritik ilmiah yang jernih. Sikap semacam ini tidak menghapus kontroversi, tetapi menolak reduksionisme yang mana tidak mengultuskan, tetapi menimbang proporsional.
Penghargaan kenegaraan adalah bahasa simbolik yang, bila diberikan, tidak menutup arsip, justru mendorong pengelolaan pengetahuan yang lebih transparan dan akuntabel bagi generasi muda. Kita bisa, bersamaan, merawat memorialisasi yang adil dan memperluas studi kritis—agar ingatan publik tidak jadi alat balas dendam ideologis, melainkan perangkat pembelajaran kewargaan. Dengan begitu, diskursus “kepahlawanan” tidak berhenti pada romantika, tetapi berfungsi sebagai kontrak moral antargenerasi saat negara memberi hormat pada kerja yang menguatkan martabat kolektif, sementara masyarakat mempertahankan disiplin refleksi. Di titik itulah, pemberian gelar menjadi bagian dari tata krama republik yang matang. Sebuah keputusan yang menyeimbangkan fakta, konteks, dan hikmah, demi memantik kesadaran akan nilai-nilai kerja sunyi yang membangun negeri.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan adalah ritus sipil yang menagih kedewasaan kolektif. Suara dari banyak pihak menunjukkan spektrum dukungan yang lahir dari logika berbeda namun saling bertaut—etika pengakuan, verifikasi historis, memori keseharian, dan pedagogi kebangsaan. Menimbang Soeharto untuk gelar Pahlawan Nasional, dalam kerangka itu, bukan keputusan emosional, melainkan uji kematangan institusi dan publik yang dikelola dengan bukti, proporsi, dan kejujuran intelektual, sehingga penghargaan ini dapat menjadi momentum rekonsiliasi memori—sebuah cara berbangsa yang tidak menutup mata pada kompleksitas, namun justru menggunakannya sebagai bekal untuk berjalan lebih tegap ke depan.
*) pemerhati kebudayaan
Post navigation